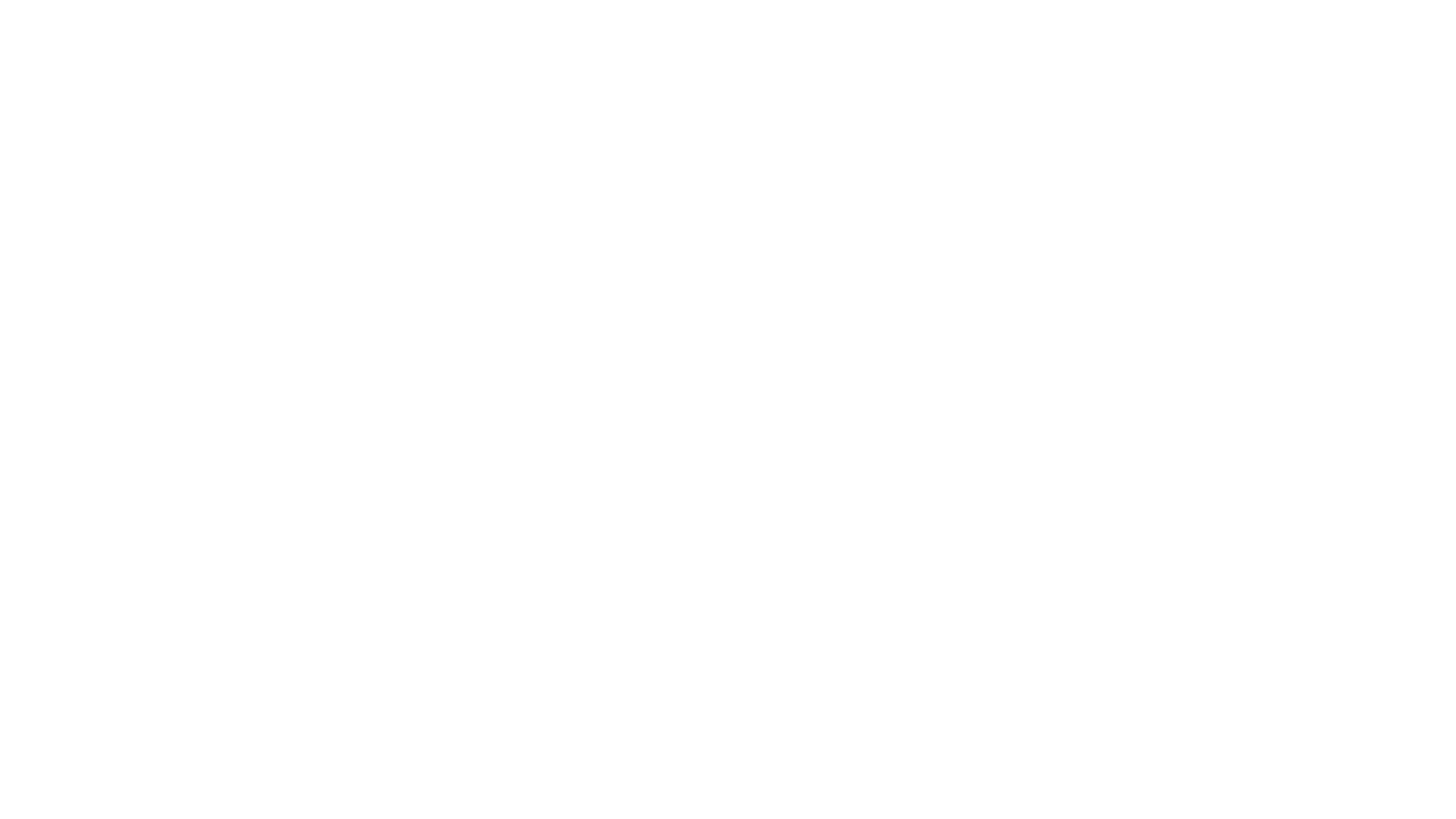Oleh: Dr. Muhsin Labin
Perjalanan pemikiran teologi Islam adalah arena yang dinamis, di mana konsep-konsep fundamental seperti kehendak bebas dan takdir ilahi diperdebatkan dengan sengit. Dari perdebatan ini, lahirlah berbagai mazhab yang tidak hanya merumuskan pandangan teologis, tetapi juga memiliki implikasi politik yang mendalam. Kisah stigmatisasi Mu’tazilah sebagai “Qadariyah” dan kebangkitan Asy’ariyah dengan doktrin “kasb” adalah cerminan bagaimana teologi dan kekuasaan saling terkait erat.
Awal Mula Qadariyah dan Mu’tazilah: Benih Kebebasan dan Pergolakan
Benih “Qadariyah” mulai tumbuh di penghujung abad pertama Hijriah di Bashrah dan Damaskus. Tokoh-tokoh seperti Ma’bad al-Juhani dan Ghaylan al-Dimasyqi adalah pelopornya. Mereka percaya bahwa manusia memiliki kehendak bebas (free will) dan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Gagasan ini muncul sebagai antitesis terhadap paham Jabariyah yang mengklaim segala sesuatu telah ditakdirkan Tuhan, sebuah narasi yang sering kali digunakan para penguasa Umayyah untuk melegitimasi kekuasaan absolut mereka dengan narasi “Ali dikhianati dan dibunuh, Al-Hasan diracun, dan Al-Husain dan keluarga serta pengikutnya dibantai karena ketentuan Tuhan”.
Pandangan Qadariyah yang menekankan akuntabilitas individu adalah ancaman langsung bagi rezim yang ingin kekuasaannya dianggap sebagai takdir ilahi. Akibatnya, para penguasa Umayyah bereaksi keras. Ma’bad al-Juhani dan Ghaylan al-Dimasyqi harus membayar mahal keyakinan mereka, menghadapi penangkapan dan bahkan hukuman mati. Sejak awal, isu takdir ini tak bisa dilepaskan dari urusan politik.
Beberapa dekade kemudian, di awal abad kedua Hijriah, lahirlah Mu’tazilah di Bashrah. Dipelopari oleh Wasil bin Atha, Mu’tazilah membangun sistem teologis yang lebih sistematis. Salah satu prinsip utama mereka adalah Al-‘Adl (keadilan Tuhan).
Bagi Mu’tazilah, Tuhan yang adil tak mungkin memaksakan perbuatan pada hamba-Nya dan kemudian menghukum mereka. Oleh karena itu, manusia pasti diberikan kebebasan untuk memilih, agar mereka bertanggung jawab penuh. Pandangan ini memiliki kemiripan yang kuat dengan Qadariyah dalam hal penekanan pada kehendak bebas manusia, namun Mu’tazilah membawa penalaran filosofis dan rasionalitas yang jauh lebih mendalam.
Stigmatisasi Mu’tazilah dan Peran Politik
Drama teologis mencapai puncaknya di era Abbasiyah. Di bawah Khalifah Al-Ma’mun (awal abad ke-3 H), Mu’tazilah meraih kejayaan. Al-Ma’mun bahkan memberlakukan “Mihnah” atau inkuisisi, memaksa para ulama untuk menerima doktrin Mu’tazilah tentang penciptaan Alquran. Ini adalah upaya jelas untuk menyatukan negara di bawah satu ideologi resmi.
Namun, roda politik berputar. Setelah masa Mihnah berakhir, Khalifah Al-Mutawakkil mengambil alih kekuasaan. Ia membalikkan kebijakan pendahulunya secara drastis, mencabut dukungan terhadap Mu’tazilah dan mendukung kembali ulama-ulama tradisional.
Di sinilah stigmatisasi Mu’tazilah sebagai “Qadariyah” menemukan lahan subur. Karena Mu’tazilah juga berpandangan tentang kehendak bebas, musuh-musuh politik dan teologis mereka—terutama para ulama tradisional yang kelak menjadi cikal bakal Ahlussunnah—dengan mudah menyatukan kedua istilah itu. Qadariyah sudah lama dicap sesat karena dianggap menolak takdir Tuhan, dan secara implisit, menolak kekuasaan penguasa yang mengklaim takdir ilahi sebagai legitimasi. Dengan menempelkan label “Qadariyah” pada Mu’tazilah, para penentangnya berhasil mendiskreditkan Mu’tazilah secara teologis, menjadikannya “menyimpang” dari ajaran Islam yang “benar.”
Stigmatisasi ini memiliki tendensi politik yang sangat jelas:
Pertama, legitimasi kekuasaan. Paham tentang takdir dan kehendak bebas selalu menjadi alat ampuh untuk melegitimasi atau mendelegitimasi kekuasaan. Penguasa yang ingin kekuasaannya tak diganggu akan mendukung paham Jabariyah, sementara kelompok yang menekankan kehendak bebas bisa dianggap mengancam otoritas.
Kedua, menekan oposisi. Memberikan cap “sesat” atau “bid’ah” pada sebuah aliran pemikiran adalah cara efektif untuk menekan perbedaan pendapat, baik intelektual maupun politik.
Ketiga, kontrol ideologi. Setiap rezim ingin mengontrol narasi dan ideologi yang beredar di masyarakat. Dengan mengasosiasikan Mu’tazilah dengan “Qadariyah” yang sudah buruk reputasinya, mereka berhasil meredam pengaruh Mu’tazilah.
Teologi Asy’ariyah: Antara Ambiguitas Doktrin “Kasb” dan Stabilitas Politik
Di tengah pergolakan teologis ini, muncullah Abul Hasan al-Asy’ari (873–936 M), pendiri mazhab Asy’ariyah. Teologi Asy’ariyah sering disebut sebagai jalan tengah, berusaha menjembatani dua kutub ekstrem: fatalisme yang dikaitkan dengan Jabariyah dan kebebasan mutlak manusia ala Mu’tazilah.
Sebelumnya, perlu dipahami bahwa “Jabariyah” dan “Qadariyah” bukanlah nama kelompok teologis formal, melainkan label polemik untuk menggambarkan pandangan ekstrem tentang takdir. Jabariyah dikaitkan dengan pandangan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan sepenuhnya oleh Allah, sehingga manusia tak memiliki kebebasan sejati. Sebaliknya, Qadariyah menekankan kebebasan manusia dalam menentukan perbuatannya, seolah-olah kehendak ilahi tidak berperan.
Al-Asy’ari berupaya merumuskan pandangan yang selaras dengan Alquran: bahwa Allah adalah Pencipta segala sesuatu, termasuk perbuatan manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Surah As-Saffat (37:96), “Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat.” Namun, ia juga menyadari bahwa menyangkal kebebasan manusia sepenuhnya dapat mengarah pada fatalisme. Dari sinilah lahir doktrin kasb, sebuah konsep yang berusaha menjaga keseimbangan antara kuasa mutlak Allah dan tanggung jawab moral manusia.
Doktrin Kasb: Jembatan antara Takdir dan Tanggung Jawab
Doktrin kasb adalah inti dari teologi Asy’ariyah, berupaya menjelaskan bagaimana manusia dapat memiliki kebebasan dalam kerangka kehendak ilahi yang mutlak:
Pertama, kuasa ilahi yang mutlak. Allah adalah Pencipta segala perbuatan manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Insan (76:30), “Kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah.” Tidak ada tindakan—baik atau buruk—yang terjadi tanpa kehendak dan kuasa-Nya.
Kedua, tanggung jawab manusia melalui kasb. Meskipun Allah menciptakan perbuatan, manusia “mengakuisisi” (kasaba) tindakan tersebut melalui kehendak parsial mereka. Misalnya, ketika seseorang bersedekah, Allah menciptakan tindakan itu, tetapi manusia memilih untuk melakukannya, sehingga berhak atas pahala. Sebaliknya, jika seseorang mencuri, ia memilih tindakan itu dan harus menanggung dosanya.
Melalui kasb, al-Asy’ari berupaya menolak pandangan fatalistik yang menyamakan manusia dengan boneka tanpa kehendak, sekaligus menegaskan bahwa manusia tetap bertanggung jawab atas perbuatannya, sebagaimana tersirat dalam Surah Al-Zalzalah (99:7-8). Dengan demikian, kasb menjadi jembatan teologis untuk memadukan dua kebenaran Alquran: kuasa Allah yang tak terbatas dan tanggung jawab moral manusia.
Paradoks Kasb: Ketegangan antara Logika dan Dogma (“Iman”)
Meski dirancang untuk menciptakan keseimbangan, doktrin kasb justru melahirkan paradoks yang sulit dipecahkan secara rasional. Jika Allah menciptakan segala perbuatan, termasuk pilihan manusia, bagaimana manusia dapat dianggap bebas dan bertanggung jawab? Bukankah kehendak manusia itu sendiri bergantung pada kuasa Allah? Frasa Arab “akhfa min kasb al-Asy’ariyyah” (lebih samar dari kasb Asy’ariyah) mencerminkan betapa sulitnya memahami konsep ini, bahkan di kalangan ulama.
Kritikus menilai kasb sebagai upaya yang dipaksakan untuk mempertahankan dua prinsip Alquran tanpa benar-benar menyelesaikan kontradiksi secara logis. Meskipun al-Asy’ari menolak fatalisme murni, penekanannya pada kuasa ilahi membuat pandangannya rentan ditafsirkan sebagai determinisme. Paradoks ini menjadi titik lemah utama Asy’ariyah dari perspektif rasionalitas filosofis, meskipun secara teologis tetap menarik bagi banyak kalangan karena kesetiaannya pada teks Alquran.
Kebangkitan Asy’ariyah dan Dukungan Kekhalifahan Abbasiyah
Kekuatan teologi Asy’ariyah tidak hanya terletak pada argumen teologisnya, tetapi juga pada dukungan politik yang signifikan dari Kekhalifahan Abbasiyah, terutama pada paruh kedua masa kekuasaannya. Konflik teologis dan Mihnah yang memecah belah masyarakat pada abad ke-9, di mana Mu’tazilah didukung oleh khalifah seperti Al-Ma’mun, Al-Mu’tasim, dan Al-Watsiq, menciptakan ketegangan besar dengan masyarakat konservatif.
Titik balik krusial terjadi pada masa Khalifah al-Mutawakkil (847-861 M), yang menghentikan dukungan terhadap Mu’tazilah dan beralih mendukung aliran tradisionalis dan Ahl al-Sunnah wal Jama’ah. Momentum ini membuka jalan bagi Asy’ariyah untuk berkembang. Abul Hasan al-Asy’ari, yang awalnya seorang Mu’tazili, beralih ke pandangan yang lebih seimbang setelah berselisih dengan gurunya, al-Jubba’i. Doktrin kasb yang ia kembangkan menawarkan solusi teologis yang menarik: menegaskan kuasa Allah sekaligus menjaga tanggung jawab manusia.
Asy’ariyah menjadi pilihan ideal bagi Abbasiyah karena beberapa alasan:
Pertama, stabilitas sosial. Penekanan pada takdir ilahi mendorong penerimaan terhadap kondisi yang ada, mengurangi potensi pemberontakan. Dengan menyatakan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, kritik terhadap penguasa dapat dianggap menentang takdir.
Kedua, legitimasi kekuasaan. Doktrin Asy’ariyah memperkuat posisi khalifah sebagai pemimpin yang dipilih Allah, terutama di tengah fragmentasi politik.
Ketiga, keseimbangan teologis. Asy’ariyah merangkul baik tradisionalis maupun elemen rasional, menjadikannya akidah yang dapat diterima oleh mayoritas umat setelah polarisasi era Mihnah.
Keempat, dukungan institusional. Dukungan konkret datang pada masa Kekaisaran Seljuk, terutama melalui Nizam al-Mulk, wazir agung yang mendirikan Madrasah Nizamiyyah. Madrasah ini menjadikan teologi Asy’ariyah sebagai kurikulum resmi, melahirkan generasi ulama seperti Imam al-Ghazali, yang memperkuat posisi Asy’ariyah dalam wacana Sunni.
Sejak menguatnya dominasi mazhab kalam Asy’ariyah dan melemahnya mazhab kalam Mu’tazilah, nasib Mu’tazilah berbalik drastis. Proses regenerasi pemikirannya terputus. Yang tersisa dari Mu’tazilah setelah itu hanyalah nama-nama para tokohnya yang disebut-sebut dalam buku-buku para teolog kontra-Mu’tazilah. Mereka “menggunjing,” membantah, dan bahkan memvonis Mu’tazilah secara absentia, tanpa ada lagi suara pembela yang signifikan dari mazhab itu sendiri. Ini adalah puncak kemenangan politik-teologis Asy’ariyah, di mana narasi dominan berhasil mengubur jejak pemikiran Mu’tazilah dari diskursus utama, menyisakannya hanya sebagai referensi negatif dalam historiografi pihak lawan.
Kesimpulan
Kisah Mu’tazilah dan stigmatisasi “Qadariyah” adalah cerminan bagaimana gagasan teologis seringkali menjadi medan pertempuran bagi perebutan kekuasaan dan hegemoni ideologi. Sementara itu, teologi Asy’ariyah, dengan doktrin kasb-nya, menawarkan solusi teologis yang berupaya menyeimbangkan kuasa ilahi dan tanggung jawab manusia, meskipun paradoks rasionalnya tetap menjadi bahan perdebatan.
Dukungan Kekhalifahan Abbasiyah, terutama melalui dinasti Seljuk, menjadikan Asy’ariyah sebagai mazhab teologi dominan dalam Islam Sunni. Dukungan ini bukan sekadar preferensi intelektual, melainkan strategi politik untuk menjaga stabilitas, legitimasi, dan persatuan umat di tengah tantangan zaman. Kisah Asy’ariyah adalah contoh bagaimana teologi dan politik dapat saling menguatkan, meskipun pertanyaan filosofis seputar kasb terus mengundang diskusi hingga kini. (*Cendekiawan Muslim)