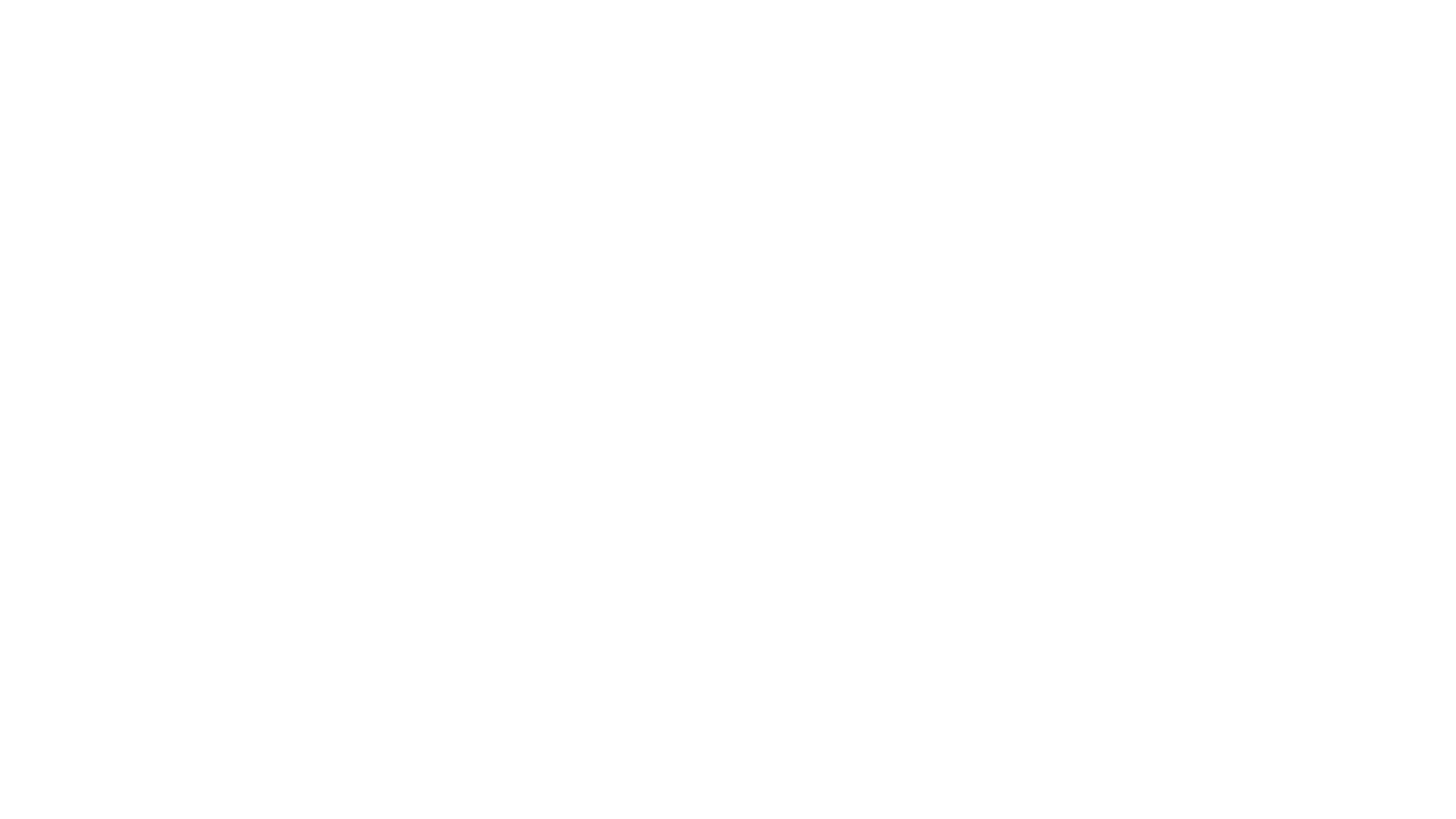Oleh: Dr. Muhsin Labib*
Prediksi Menteri Kesehatan tentang 28 juta penduduk Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan mental menemukan pantulannya yang nyaris presisi di ruang publik hari ini. Internet bukan lagi sekadar medium komunikasi, melainkan arena katarsis bagi mereka yang kehilangan kendali diri. Tuhan, agama dan politik tidak diperdebatkan dengan nalar, melainkan diteriakkan dengan syahwat. Tuhan yang diimani kelompok lain dicaci dengan semangat tanpa iman; sementara gagasan ketuhanan diludahi dengan militansi kosong—tanpa dalil, tanpa argumen, tanpa jejak bahwa logika pernah mampir di sana.
Di negeri ini, isu tertentu bisa menjadi api yang menyala bertahun-tahun, bukan karena kerumitannya, melainkan karena absennya kehendak untuk memadamkannya. Kontroversi telah berubah menjadi candu; amarah menjadi hiburan massal. Isu yang sama, kemarahan yang serupa, dan figur-figur yang itu-itu saja, berputar dalam lingkaran setan tanpa pernah memetik pelajaran. Luka lama tidak dibuka untuk disembuhkan, melainkan untuk memastikan rasa sakitnya tetap segar—cukup perih untuk dijadikan alasan memaki dan merasa “hidup”.
Perdebatan telah kehilangan etika intelektual. Agama diperlakukan sebagai amunisi, bukan kompas nurani. Kelompok etnik direndahkan dengan “keberanian pengecut” yang hanya tumbuh subur di balik layar. Perbedaan pandangan ditolak bukan dengan tandingan argumen, melainkan dengan volume suara. Intoleransi menjadi istilah yang terlalu sopan untuk menggambarkan kebencian murni yang kehilangan logika—sebuah kemarahan patologis yang merayakan dirinya sendiri. Di titik ini, diagnosis kejiwaan bukan lagi wacana akademik, melainkan kebutuhan darurat nasional.
Internet menyediakan panggung yang sempurna karena jarak memberi ilusi kekebalan. Tanpa risiko fisik, seseorang merasa sah memuntahkan apa saja, seolah anonimitas adalah lisensi moral untuk menjadi sampah sosial. Kekasaran diklaim sebagai kejujuran. Kedangkalan berpikir dipoles sebagai keberanian. Logika ditinggalkan dengan sadar, laiknya pengembara yang membuang kompas lalu bertepuk tangan karena berhasil tersesat.
Pola ini beriringan dengan romantisme masa lalu yang konyol. Kejayaan lampau dipoles sebagai identitas permanen, padahal yang tersisa hanyalah slogan yang diulang-ulang seperti mantra gagal. Ketidakmampuan menjelaskan posisi hari ini ditutupi dengan dongeng kehebatan nenek moyang yang sudah lama usai. Nostalgia digunakan sebagai topeng untuk menyamarkan ketidakberdayaan kolektif.
Namun, di bawah hiruk-pikuk digital, terdapat lapisan yang lebih sunyi sekaligus lebih busuk: korupsi yang sistemik dan penyimpangan moral oleh mereka yang justru disumpah sebagai penjaga moral. Di sini, gangguan mental tidak hadir sebagai teriakan, melainkan sebagai kemampuan luar biasa untuk membenarkan kejahatan. Korupsi dibaptis menjadi “efisiensi”. Pelecehan disamarkan sebagai “budaya”. Pencurian dibungkus dengan presentasi dan prosedur formal. Inilah gangguan yang terstruktur—berdasi, berpendidikan, dan berekening aman.
Apa yang kita tonton hari ini adalah krisis cara berpikir dan kegagalan pengelolaan emosi dalam skala masif. Kebencian tegak tanpa alasan, masa lalu menggantikan kenyataan, dan kejahatan tampil santun melalui sistem. Masyarakat kehilangan kemampuan paling dasar dalam peradaban: membedakan yang benar dari yang keliru, yang layak dari yang hina, serta yang rasional dari yang sekadar luapan amarah.
Angka 28 juta bukan sekadar statistik di atas kertas. Ia adalah cermin retak dari kegagalan kita mengelola perbedaan. Di balik setiap cacian tanpa argumen, berdiri para psyco yang batinnya sedang runtuh, namun menjadikan ruang publik sebagai tempat pembuangan limbah traumanya. Yang paling tragis, mereka mengira sedang berpikir kritis dan membela kebenaran, padahal yang terjadi hanyalah teriakan dalam gelap—lalu mereka keliru menganggap gema suaranya sendiri sebagai pembenaran dari langit.
Inilah ironi zaman digital: akses informasi semakin luas, namun jarak dengan pengetahuan semakin jauh. Kesempatan berbicara semakin mudah, namun kemampuan berpikir semakin langka. (Cendekiawan Muslim)