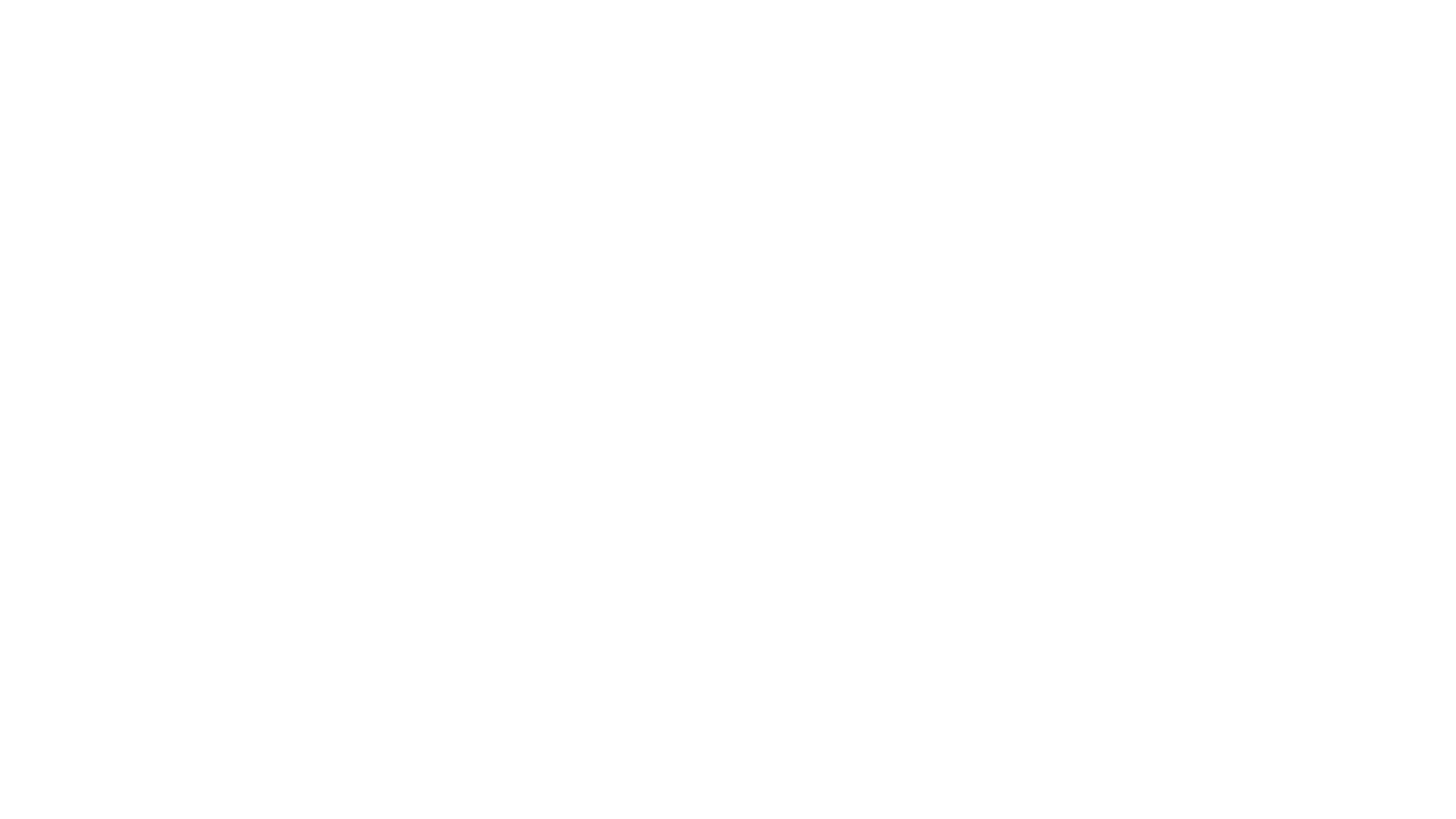Oleh: Dr. Muhsin Labib*
Beberapa kali Donald Trump secara terbuka melontarkan ancaman serangan militer terhadap Iran. Retorika tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan disertai demonstrasi kekuatan yang dirancang secara simbolik dan strategis: pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln, armada tempur berskala besar, serta manuver militer di kawasan Timur Tengah yang berdekatan langsung dengan wilayah perairan Iran. Bahasa yang dipergunakan bukan bahasa diplomasi, melainkan bahasa intimidasi geopolitik—sebuah teater kekuasaan yang bertujuan membangun citra dominasi Amerika Serikat sebagai pusat kuasa global.
Sebagian besar warga dunia, khususnya mereka yang terikat secara ideologis pada mitologi superioritas Barat, meyakini bahwa Trump benar-benar akan melumat Iran dan menggulingkan Republik Islam. Iran dikonstruksikan sebagai ancaman global, sementara Amerika ditempatkan sebagai otoritas moral dunia yang merasa memiliki mandat historis untuk mengatur tatanan internasional. Narasi ini bukan lahir dari pembacaan objektif realitas geopolitik, melainkan dari reproduksi panjang propaganda hegemoni yang menormalisasi dominasi sebagai kebajikan.
Namun sejarah tidak pernah tunduk pada fantasi kekuasaan. Trump tiba-tiba mengubah haluan. Retorika konfrontatif bergeser menjadi bahasa perundingan. Ancaman berubah menjadi diplomasi. Perubahan ini bukan refleksi kedewasaan politik, apalagi kesadaran etis, melainkan konsekuensi dari kalkulasi kekuasaan yang rasional dan dingin.
Iran bukanlah negara perifer tanpa daya. Ia memiliki struktur negara yang kokoh, basis militer yang mapan, jaringan regional yang luas, serta aliansi strategis global yang nyata. Perang terhadap Iran berarti biaya ekonomi yang luar biasa besar, risiko politik yang destruktif, dampak elektoral yang serius, serta potensi instabilitas kawasan yang dapat membakar seluruh Timur Tengah. Pada tingkat global, konfigurasi kekuatan multipolar—dengan kehadiran Rusia, China, dan poros non-Barat—membuat perang tidak lagi menjadi panggung sepihak Amerika. Pada titik ini, ancaman tidak lagi fungsional sebagai instrumen dominasi. Ia berubah menjadi beban struktural.
Namun di luar seluruh variabel geopolitik tersebut, muncul satu faktor yang jauh lebih menentukan dan tak terduga: kehancuran dari dalam sistem kekuasaan itu sendiri. Bukan melalui konfrontasi militer, melainkan melalui krisis legitimasi, kehancuran reputasi, dan delegitimasi moral elite global. Epstein’s files menjadi simbol paling nyata dari ledakan internal tersebut.
Ia bukan senjata fisik, tetapi senjata simbolik. Ia tidak menghancurkan kota, tetapi menghancurkan kredibilitas. Ia tidak merobohkan bangunan, tetapi merobohkan legitimasi. Ia tidak meluluhlantakkan infrastruktur, tetapi meretakkan fondasi moral kekuasaan global. Inilah bentuk kekuatan non-militer yang paling berbahaya bagi sistem hegemonik modern: kehancuran kepercayaan.
Trump sendiri memperlihatkan perubahan yang signifikan. Gestur tubuhnya kehilangan aura dominasi. Bahasa politiknya melemah. Ekspresi publiknya memperlihatkan kegelisahan yang sulit disamarkan. Protes muncul di berbagai ruang publik. Opini global bergejolak. Media dipenuhi spekulasi. Nama-nama besar diperbincangkan. Figur-figur berpengaruh digunjing. Dan yang paling mencolok, sebagian besar nama yang beredar berada dalam orbit Zionisme politik dan imperialisme Amerika, baik di Amerika maupun Eropa, menandai bahwa krisis ini bukan personal, melainkan sistemik.
Terlepas dari benar atau salahnya isi dokumen-dokumen tersebut, satu fakta tak terbantahkan: ia menciptakan aib struktural. Dalam politik global, aib struktural sering kali jauh lebih destruktif daripada kekuatan militer. Senjata menghancurkan tubuh, tetapi aib menghancurkan legitimasi. Perang merusak wilayah, tetapi krisis moral merusak sistem. Infrastruktur dapat dibangun ulang, tetapi kepercayaan yang runtuh hampir mustahil dipulihkan sepenuhnya.
Di sinilah ironi sejarah mencapai puncaknya. Hegemoni yang terbiasa menghadapi musuh eksternal justru terguncang oleh retakan internal. Kekuasaan yang merasa kebal terhadap tekanan luar menjadi rapuh oleh kontradiksi moralnya sendiri. Imperium tidak runtuh karena serangan lawan, tetapi karena kegagalan menjaga fondasi etiknya.
Inilah yang dapat disebut sebagai kemenangan metafisik Iran. Bukan kemenangan militer, bukan kemenangan strategis konvensional, dan bukan kemenangan geopolitik klasik, melainkan kemenangan simbolik dan struktural. Tatanan hegemonik global melemah bukan karena tekanan eksternal, tetapi karena kehancuran legitimasi internalnya sendiri.
Sejarah mengajarkan satu hukum yang konsisten: kekaisaran tidak selalu runtuh karena serangan luar; sering kali ia hancur karena pembusukan dari dalam. Dalam konteks ini, Iran tidak menang sebagai kekuatan senjata, melainkan sebagai simbol resistensi terhadap tatanan dominasi global—bahwa perubahan besar dalam sejarah peradaban lebih sering lahir dari krisis makna, delegitimasi moral, dan keruntuhan kepercayaan, daripada dari dentuman senjata.
“Jangan ramah kepada orang yang menganggap keramahanmu sebagai pertanda lemah, takut dan butuh.” Iran rupanya menjadikan perkataan Ali bin Abi Talib ini sebagai platform sikap dalam psy war ini. (*Cendekiawan Muslim)