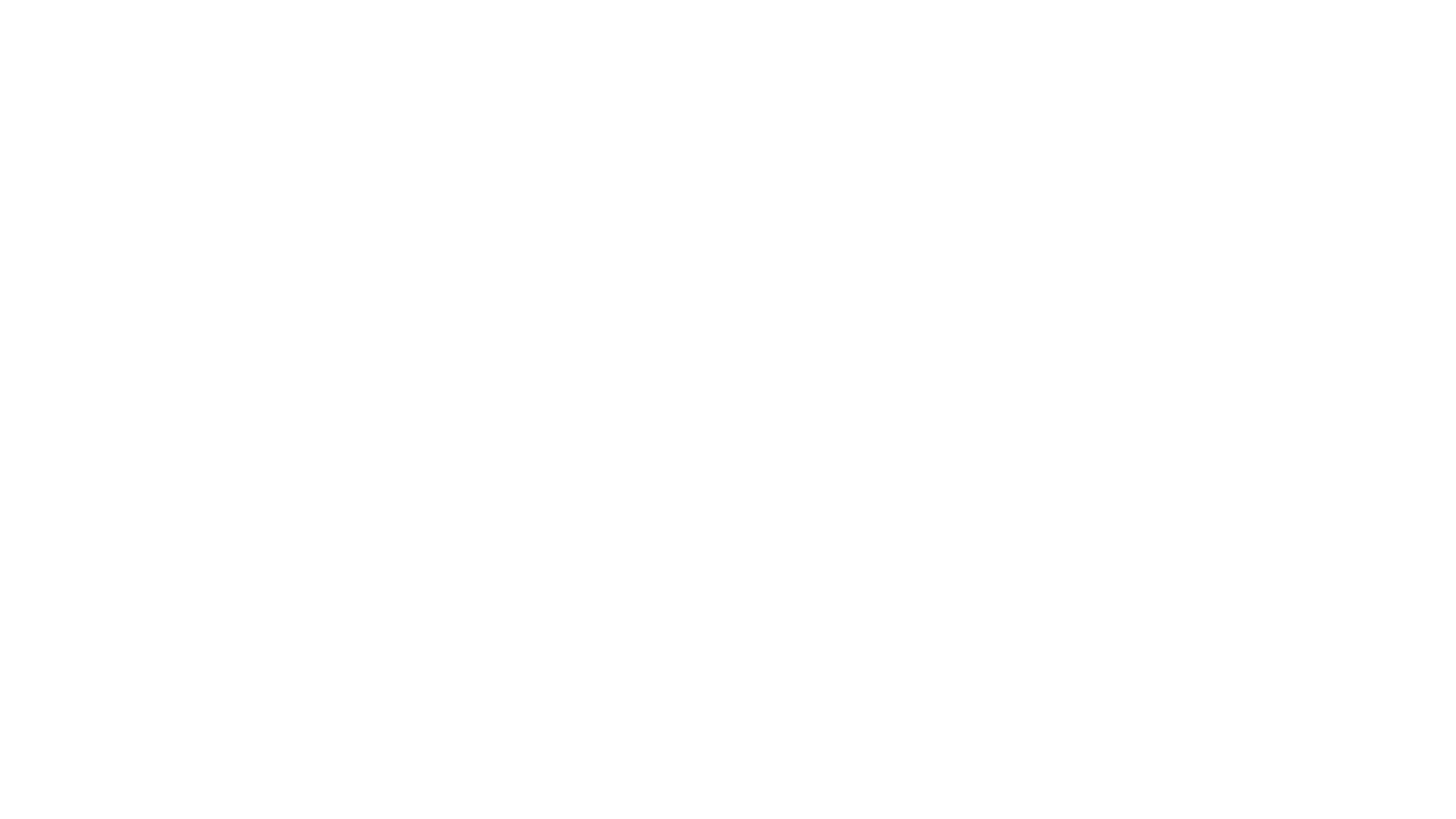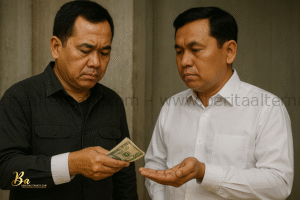Oleh: Wahyu Tri Prayogi*
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah bagian dari fokus masalah kesehatan yang menyangkut pekerja dan interaksinya terhadap lingkungan kerja. K3 rumah sakit merupakan rangkaian upaya dalam menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja rumah sakit, pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit dari potensi bahaya yang dapat timbul akibat aktivitas pelayanan kesehatan (Diannita et al., 2020).
Dasar hukum yang mendasari K3 di rumah sakit terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan lebih spesifik diatur dalam Permenkes RI Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).
K3RS merupakan upaya menjamin dan melindungi pekerja, pasien, pengunjung, dan lingkungan rumah sakit untuk mencegah kejadian kecelakaan kerja di rumah sakit (Peraturan Menteri Kesehatan, 2016).
Rumah sakit sebagai salah satu pusat layanan fasilitas kesehatan tertinggi dalam menyediakan upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, tentunya tidak terlepas dari berbagai risiko. Kegiatan operasional yang dilakukan di rumah sakit dihadapkan dengan risiko yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan seperti risiko fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikososial (Nova et al., 2020).
Sebuah penelitian Rudyarti (2017) menggambarkan terdapat kaitan yang signifikan antara keselamatan dan kesehatan pekerja dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada insiden kecelakaan di tempat kerja, di mana pengetahuan tentang keselamatan berkontribusi 16% dan penggunaan APD berkontribusi sebesar 22% terhadap insiden kecelakaan kerja. World Health Organization (WHO) mengidentifikasi salah satu risiko pekerjaan yang dihadapi tenaga kesehatan yaitu risiko transmisi infeksi melalui tusukan jarum yang terkontaminasi.
Prevalensi yang tinggi pada penyakit akibat kerja seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV menegaskan pentingnya penerapan tindakan yang terstandar K3 rumah sakit. WHO menekankan bahwa tindakan pencegahan merupakan kunci untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan, berupa penerapan standar K3 yang efektif di rumah sakit (Pradana & Iqbal, 2024).
Selain itu, ranah rumah sakit juga menghadapi risiko lain seperti kecelakaan kerja meliputi insiden kebakaran, sengatan listrik, banjir, runtuhan bangunan, serta keracunan gas karbon monoksida.
Secara nasional, Indonesia telah mengintegrasikan manajemen K3 dalam sebuah mekanisme akreditasi rumah sakit. Hal tersebut menekankan tanggung jawab manajemen rumah sakit dalam melakukan upaya kesehatan preventif, pengobatan penyakit, peningkatan kesehatan pekerja, dan perlindungan dari masalah kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan.
Meskipun penerapan standar K3 di rumah sakit menjadi perhatian khusus, tetapi masih banyak didapati tantangan dalam implementasinya. Penelitian yang dilakukan Saputra menunjukkan ada kendala dalam implementasi praktik K3 di lapangan. Meski kesadaran akan risiko sudah ada, tetapi pemahaman petugas rumah sakit yang kurang tentang tindakan pencegahan yang terstandar K3 masih menjadi masalah.
Studi pada 108 rumah sakit mengungkapkan masih kurangnya pemahaman dan kesadaran akan tindakan pencegahan yang terstandar. Hal tersebut menunjukkan pentingnya upaya dalam peningkatan pengetahuan dan kesadaran terkait praktik K3 masih sangat dibutuhkan.
Beberapa faktor yang diidentifikasi dapat menghambat penerapan sistem K3 rumah sakit, yang pertama faktor manajemen dan kebijakan rumah sakit. Hal tersebut berkaitan dengan pandangan pimpinan yang fokus pada layanan medis dan finansial, sehingga aspek K3 diabaikan. Tanpa komitmen, kebijakan hanya bersifat formalitas tanpa implementasi nyata. Akibatnya ada rumah sakit yang sudah memiliki SOP K3, tetapi tidak dijalankan secara konsisten.
Selain itu, di rumah sakit yang belum mengintegrasikan sistem K3 dengan manajemen mutu dan keselamatan pasien mengakibatkan program menjadi tumpang tindih dan kurang sinkron antarunit.
Faktor kedua yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan tenaga medis, akibatnya mengabaikan prosedur keselamatan dalam bekerja. Hal tersebut juga berkaitan dengan pengetahuan tenaga kesehatan. Contohnya masih banyak yang tidak memahami prosedur evakuasi, pencegahan infeksi, serta pengelolaan limbah. Adanya beban kerja yang tinggi seperti shift kerja yang panjang dapat menyebabkan kelelahan dan meningkatkan risiko kecelakaan akibat human error.
Faktor ketiga yaitu ketersediaan sarana dan prasarana seperti APD yang terbatas, khususnya golongan APD yang sekali pakai. Akibat keterbatasan tersebut, seringkali ditemukan penggunaan ulang APD sekali pakai.
Sarana berupa peralatan medis yang kurang dalam perawatan seperti ventilator atau sistem kelistrikan dapat berisiko membahayakan keselamatan pasien dan tenaga medis. Selain itu, sistem pengelolaan limbah medis yang kurang optimal, seperti limbah yang masih dibuang dengan cara yang tidak sesuai standar.
Faktor keempat yaitu lingkungan kerja yang padat aktivitas seperti banyak pasien dan peralatan yang dirawat dalam ruangan yang kecil, sehingga rawan risiko biologis seperti terjadinya infeksi silang serta sulit dalam mengatur alur kerja aman (pemindahan pasien). Selain itu, kualitas lingkungan fisik yang rendah berupa pencahayaan kurang, ventilasi tidak memadai, serta kebisingan dapat mengganggu aktivitas medis.
Faktor kelima yaitu psikososial yang berkaitan dengan stres kerja atau burnout di mana kondisi psikologis yang membuat tenaga medis berisiko lalai. Kemudian, kurangnya keterlibatan pasien dan keluarga berupa pemberian edukasi tentang peran dalam menjaga keselamatan selama di lingkungan rumah sakit.
Faktor yang terakhir yaitu regulasi dan pengawasan internal berupa audit K3 yang jarang dilakukan serta tidak adanya monitoring rutin terkait SOP pelaksanaan K3 rumah sakit. Pengawasan eksternal melalui Kemenkes atau dinas kesehatan yang kurang ketat juga menjadi faktornya, akibatnya rumah sakit abai terhadap program K3RS. (*Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman)
Referensi
Diannita, R., Indasah, I., & Siyoto, S. (2020). Analysis of Work Accidents Based on K3 Knowledge and Work Behavior at Muhammadiyah Hospital in Ponorogo. Journal for Quality in Public Health, 3(2), 383–389. https://doi.org/10.30994/jqph.v3i2.87
Peraturan Menteri Kesehatan, Pub. L. No. 38, 3 56 (2016). https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf%0Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation, society and inequalities(lsero).pdf%0Ahttps://www.quora.com/What-is-the-dif
Nova, A., Mutmainah, S. ., & Angelia, I. (2020). Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Program Keselamatan Kerja Di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh. Jurnal Kesehatan Medika Saintika, 11(2), 237–246.
Pradana, F. K., & Iqbal, M. (2024). Program Keselamatan dan Kesehatan di Rumah Sakit: Evaluasi Sistematis Implementasi dan Strategi Peningkatan. Journal Occupational Health Hygiene And Safety, 2(1), 202–221.
Rudyarti, E. (2017). Hubungan Pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sikap Penggunaan Alat Pelindung Diri dengan Kejadian Kecelakaan Kerja. Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health, 2(1), 31–43.