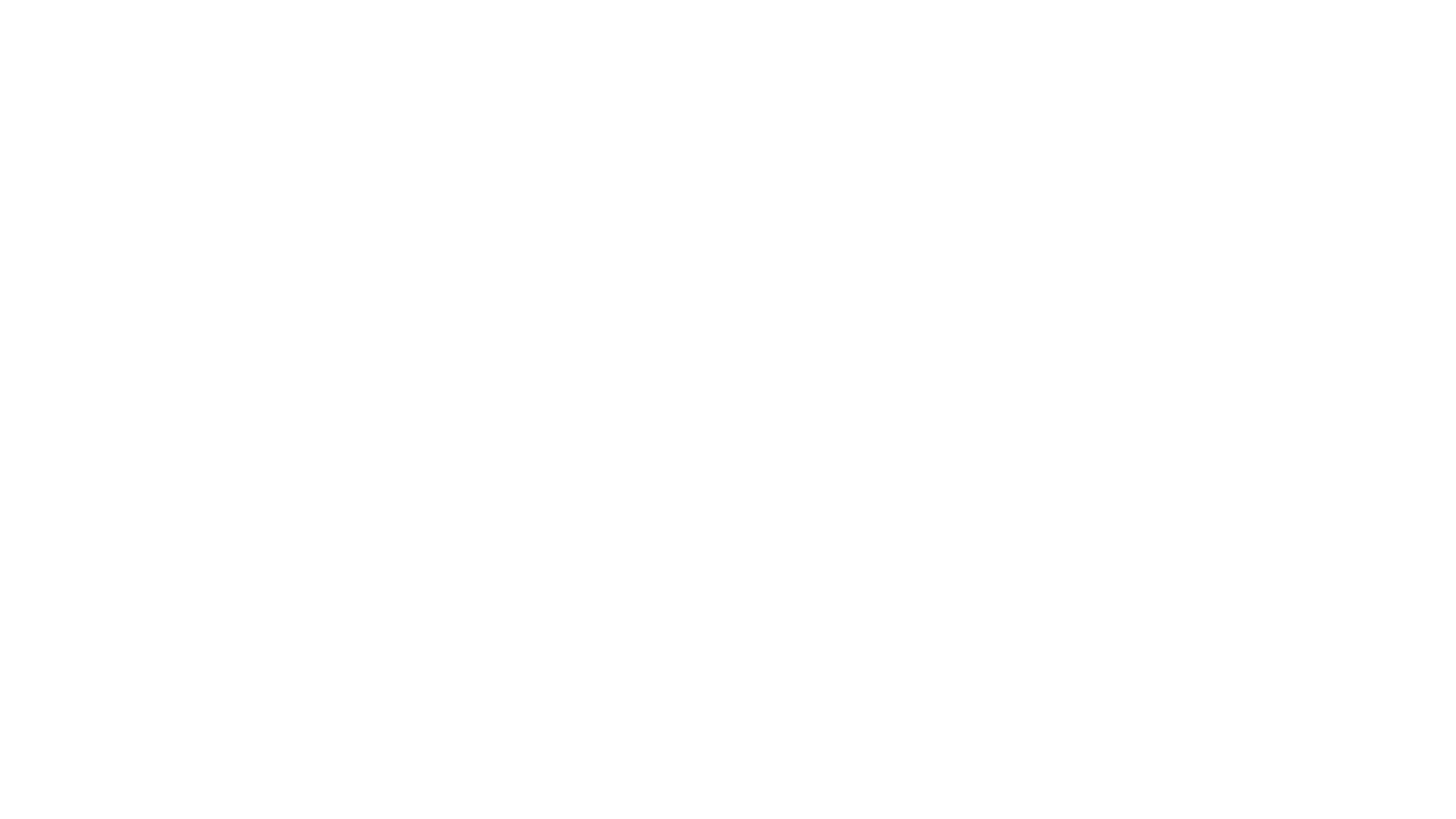Oleh: Dr. Muhsin Labib*
Sirene meraung, namun tak mampu menahan hujan proyektil balistik dan jelajah Iran yang menghantam pangkalan-pangkalan vital Amerika Serikat di Qatar dalam operasi “Bisyarah Al-Fath”—kabar gembira kemenangan. Ledakan mengguncang bumi, api menari di horizon, dan asap hitam mengepul bagai isyarat malapetaka. Ini bukan sekadar serangan militer; ini adalah gempa geopolitik yang mengubur status quo dan mengguncang dunia. Iran menjadi kekuatan baru yang berhadapan sendirian dengan aliansi dunia kotor di bawah komando AS.
Di kawasan Teluk, gelombang kejut operasi ini membakar segalanya. Militer menjadi arena pertaruhan nyawa dan kehormatan. Serangan ini adalah deklarasi perang terbuka, memaksa Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Donald Trump yang dikenal impulsif, untuk membalas dengan kekuatan penuh. Namun, tindakan Trump—yang mengandalkan pendekatan keras, serangan udara massal, atau sanksi ekonomi yang lebih brutal—bisa menjadi bumerang.
Iran bukanlah negara biasa. Rakyatnya bukan mainstream. Sistem teokrasi-revolusionernya, yang berpijak pada ideologi filosofis mistik yang mendalam, terutama di ambang peringatan Asyura, menyalakan semangat pengorbanan dan martirdom yang tak tertandingi. Asyura, yang memperingati pengorbanan Imam Husain, bukan sekadar ritual; ia adalah nyala api spiritual yang membakar jiwa rakyat Iran, mengubah setiap serangan terhadap mereka menjadi panggilan suci untuk melawan. Ditambah dengan nasionalisme Iran yang membara—akarnya tertanam dalam sejarah peradaban Persia yang bangga—setiap agresi Trump justru dapat menyatukan rakyat Iran, dari jalanan Teheran hingga desa-desa terpencil, dalam tekad baja untuk menentang.
Serangan militer yang gegabah atau sanksi yang mencekik hanya akan memperkuat narasi Iran sebagai benteng perlawanan melawan hegemoni Barat, menggalang dukungan domestik dan simpati global, terutama di kalangan “Axis of Resistance” seperti Hizbullah, milisi Syiah Irak, dan Ansarallah Yaman.
Eskalasi militer menjadi keniscayaan. Pertempuran udara, serangan siber, dan konflik laut akan mengisi hari-hari di Teluk. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, terperangkap dalam kepanikan, akan memperkuat pertahanan dan memohon perlindungan Amerika, namun ketakutan menjadi sasaran berikutnya menghantui mereka.
Sementara itu, ekonomi Teluk ambruk. Selat Hormuz, nadi perdagangan minyak dunia, terancam. Harga minyak melonjak ke angka yang tak terbayangkan, memicu inflasi global dan resesi yang menghancurkan. Negara-negara Teluk, yang bermimpi tentang kota-kota megah, menyaksikan pasar saham mereka runtuh, proyek-proyek ambisius terkubur di bawah debu krisis.
Geopolitik kawasan berguncang. Iran, meski rentan, bangkit sebagai raksasa regional yang berani menantang Amerika secara langsung. Prestisenya di kalangan kelompok perlawanan meningkat, namun risikonya besar; ia kini menjadi target kemarahan global. Amerika, di sisi lain, menghadapi krisis kredibilitas.
Tindakan Trump yang keras bisa mempercepat keretakan aliansi dengan negara-negara Teluk, yang mulai mempertanyakan keandalan perlindungan Amerika. Israel, terperangkap dalam ancaman eksistensial, menghadapi kemungkinan perang multi-front dengan Hizbullah dan Iran, menghubungkan konflik Gaza dengan perang regional yang lebih luas. Negara-negara Teluk, terjepit antara ancaman Iran dan ketidakpastian Amerika, mungkin tergoda untuk merangkak menuju perundingan rahasia dengan Teheran, mencari stabilitas di tengah badai. Keretakan dalam Gulf Cooperation Council mengintai, menambah lapisan kekacauan.
Dunia global pun tak luput dari guncangan. Ekonomi ambruk di bawah tekanan hiperinflasi, krisis energi, dan gangguan rantai pasok. Negara-negara berkembang tersapu kelaparan dan kemiskinan, sementara pasar keuangan global bergoyang dalam volatilitas ekstrem.
Di ranah diplomasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa lumpuh, kredibilitasnya luntur. Kekacauan ini mempercepat pergeseran kekuatan global, dengan China dan Rusia mengisi kekosongan yang ditinggalkan Amerika yang terkuras. Perang teknologi, dari drone hingga serangan siber, menjadi wajah konflik masa depan, mengancam melumpuhkan peradaban modern.
Operasi “Bisyarah Al-Fath” adalah korek api di gudang mesiu Timur Tengah, dengan percikan yang menyebar ke seluruh dunia. Tindakan Trump, yang menganggap Iran sebagai musuh biasa, akan terpukul oleh realitas sistem dan ideologi Iran yang unik, diperkuat oleh semangat Asyura, Mahdisme dan nasionalisme yang terukir sejak sebelum Masehi.
Mengapa Qatar?
Pada tanggal 23 Juni 2025, langit di atas gurun Qatar, yang biasanya tenang dengan lalu lintas udara rutin, terkoyak oleh hujan baja dan api dalam formasi indah yang menghunjam Pangkalan Udara Al Udeid, benteng terkuat Angkatan Udara Amerika Serikat di jantung Timur Tengah, yang berdiri megah di tanah Qatar.
Pemilihan Al Udeid bukan kebetulan atau sekadar target yang mudah dijangkau. Ini adalah kalkulasi strategis yang dalam, menusuk tepat ke pusat jaringan kekuatan yang dianggap Teheran sebagai ancaman eksistensial. Setiap rudal yang menghantam landasan pacu atau hanggar di pangkalan raksasa itu membawa pesan geopolitik yang menggetarkan:
Pertama, di Suriah, Qatar menuangkan dana dan Turki menyuplai senjata ke kelompok-kelompok teroris sadis ekstremis yang mengklaim khilafah, seperti Hayat Tahrir al-Sham pimpinan al-Julani. Tindakan kedua negara ini memutus urat nadi logistik senjata bagi Hizbullah di Lebanon. Menghantam Al Udeid adalah tamparan keras bagi Doha—peringatan bahwa sepak terjangnya di Suriah tidak akan dibiarkan begitu saja.
Kedua, Qatar dan Turki bermain api ganda dalam isu Palestina. Bersama Turki, Qatar berusaha menjinakkan sayap militan Hamas. Serangan ke Al Udeid adalah cambuk bagi Qatar—isyarat keras bahwa upaya memoderasi, apalagi mengebiri, semangat perlawanan Hamas yang menjadi bagian dari “Poros Perlawanan” adalah pengkhianatan yang akan dibayar mahal di halaman belakangnya sendiri.
Ketiga, serangan ke Al Udeid adalah peringatan geopolitik bagi Qatar bahwa kedekatan Doha yang mesra dengan Amerika Serikat dan, secara diam-diam maupun terang-terangan, dengan Israel, telah melampaui batas toleransi. Serangan ini adalah teriakan di wajah Qatar untuk menjauh dari orbit Washington dan Tel Aviv, atau menghadapi konsekuensi yang semakin menghancurkan.
Keempat, Al Udeid bukan sekadar pangkalan; ia adalah otak militer AS di kawasan. Serangan ini adalah pukulan langsung terhadap kemampuan AS untuk membela dan memberdayakan Israel. Menghancurkan (atau melumpuhkan) Al Udeid berarti memotong urat nadi utama dukungan operasional AS bagi Zionis.
Kelima, serangan ini adalah pertunjukan kekuatan yang ditujukan ke seluruh penjuru dunia. Di tengah eskalasi mematikan dengan AS dan Israel, Iran tidak hanya ingin membalas, tetapi juga mendemonstrasikan kemampuannya untuk menyerang target Amerika yang paling dijaga di jantung kawasan. Serangan ini adalah iklan militer yang dramatis, dirancang untuk mengangkat posisi tawar Iran sekaligus menegaskan klaimnya sebagai kekuatan global alternatif—sebuah kutub baru yang berdiri tegak di luar bayang-bayang hegemoni AS, setara dengan Rusia dan China yang diam-diam mengamati. Iran menyatakan: Dunia tidak lagi monopoli Barat.
Serangan 23 Juni 2025 bukan sekadar insiden militer. Ia adalah babak baru dalam konstelasi regional dan global. Iran terluka, tetapi jauh dari takluk; ia bangkit dengan kemarahan yang terfokus dan senjata yang siap menyala, siap mengubah peta kekuatan regional dan menggetarkan fondasi tatanan dunia yang ada.
Dengan serangan ini, Iran ingin menegaskan bahwa secuil luka yang dialaminya takkan berlalu tanpa balas. Iran yang terluka di jelang Asyura mempersilakan AS dan sekutunya di Eropa dan dunia Arab untuk melakukan rapat darurat sebanyak mungkin. Iran yang cukup lama bersabar menanti bangkitnya kesadaran kolektif umat Islam untuk bersatu menghadapi musuh bersama kini memberi kesempatan kepada netizen di media sosial untuk berdebat, mendukung atau menentang, memuji atau mencemooh, mengaitkannya dengan agama, mazhab, atau narasi apa pun. (*Cendekiawan Muslim)