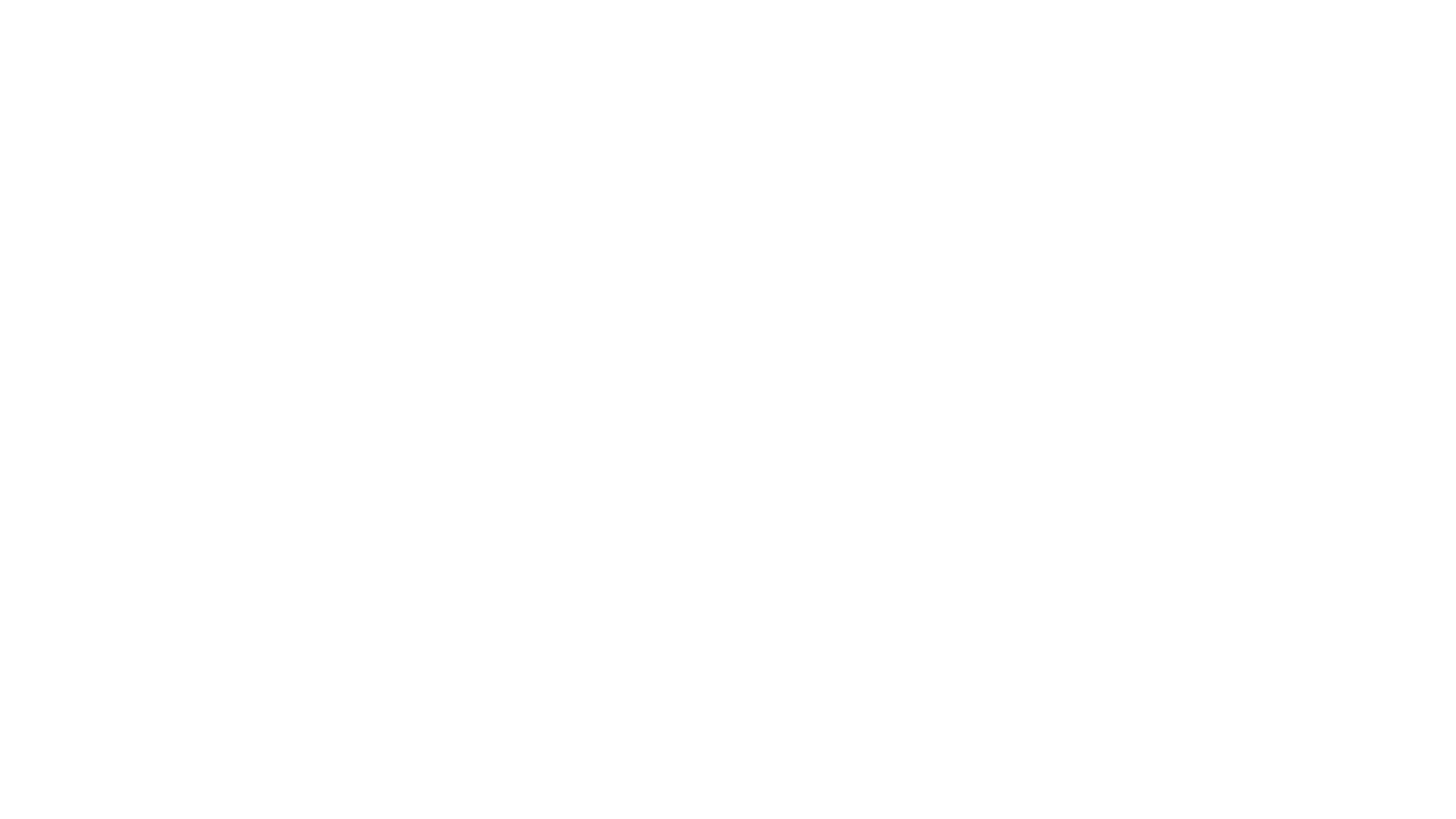Oleh: Hendra Gunawan*
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemajuan tidak semata diukur dari megahnya Proyek Strategis Nasional (PSN), besarnya nilai investasi, atau tingginya deretan jabatan yang hadir dalam sebuah acara kenegaraan. Kemajuan sejati justru tercermin dari adab, penghormatan, dan kebijaksanaan dalam memperlakukan nilai-nilai luhur yang telah hidup jauh sebelum republik ini berdiri.
Pada hari Senin, 12 Januari 2026, bertepatan dengan pelaksanaan peresmian PSN Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Pertamina Balikpapan, yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terselip sebuah peristiwa yang mengusik rasa keadilan kultural masyarakat adat. Dalam rangkaian kegiatan kenegaraan tersebut, Yang Mulia Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Sultan Aji Muhammad Arifin, justru ditempatkan pada barisan belakang tamu undangan, sebuah penempatan yang tidak sepenuhnya mencerminkan penghormatan terhadap kedudukan, marwah adat, serta nilai sejarah luhur yang beliau sandang.
Peristiwa ini telah menorehkan kekecewaan mendalam di hati masyarakat adat Kutai dan masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya. Kekecewaan tersebut bukan lahir dari keinginan untuk diistimewakan, melainkan dari rasa luka kultural akibat adab yang terpinggirkan, baik karena kelalaian maupun karena sikap abai yang terselubung dalam prosedur protokoler.
Perlu dipahami secara jernih bahwa Sultan Kutai bukanlah sekadar tamu undangan biasa, dan bukan pula simbol seremoni semata. Beliau adalah penjaga marwah sejarah, adat, dan identitas peradaban di tanah Kutai Kartanegara, sebuah peradaban yang telah ada jauh sebelum negara modern ini terbentuk. Mengabaikan posisi kehormatan beliau sama artinya dengan mengabaikan sejarah panjang yang menjadi fondasi kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.
Kekecewaan atas peristiwa tersebut secara terbuka dan santun telah disampaikan oleh berbagai tokoh adat, tokoh pemuda, serta organisasi masyarakat adat di Kalimantan Timur. Suara-suara ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan sebagai ikhtiar menjaga martabat adat dan mengingatkan negara agar tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri.
Adab seharusnya mendahului protokol, bukan sebaliknya. Ketika protokol berjalan tanpa rasa, tanpa kearifan lokal, dan tanpa penghormatan terhadap adat setempat, maka yang tercipta bukan keteraturan, melainkan kekosongan makna. Kekeliruan semacam ini kerap lahir dari pola pikir yang menempatkan jabatan administratif di atas nilai budaya, seolah-olah kehormatan hanya ditentukan oleh struktur kekuasaan, bukan oleh jasa sejarah dan kebesaran peradaban.
Kritik yang disampaikan para tokoh adat Kutai sejatinya adalah kritik yang beradab. Tidak disertai hujatan, tidak pula dibungkus amarah. Yang ada hanyalah permintaan sederhana namun bermakna: perlakukan adat dengan hormat, tempatkan nilai lokal pada posisi yang semestinya, dan jangan mengulang kekeliruan yang sama di masa depan. Kritik seperti ini seharusnya disambut dengan kebesaran jiwa dan kerendahan hati.
Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, sudah sepatutnya setiap penyelenggara negara memahami bahwa menghormati adat merupakan bagian tak terpisahkan dari menjaga persatuan nasional. Kesombongan dalam bentuk apa pun, baik kesombongan kekuasaan, jabatan, maupun prosedur, pada akhirnya hanya akan menciptakan jarak antara negara dan rakyatnya. Dan jarak kultural tersebut, bila dibiarkan, akan melahirkan luka yang dalam.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan individu atau institusi tertentu. Ini adalah cermin bersama, agar ke depan para pejabat, penyelenggara kegiatan kenegaraan, dan pengambil kebijakan lebih peka, lebih bijaksana, serta lebih beradab dalam memahami siapa yang mereka hadapi dan di tanah mana mereka berpijak.
Melalui peristiwa dalam kegiatan peresmian RDMP Balikpapan tersebut, kami mengajak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kembali meneguhkan komitmen moral dalam memimpin negeri yang majemuk. Kepemimpinan bukan hanya soal kewenangan dan kebijakan, tetapi juga tentang keteladanan dalam menghormati nilai-nilai luhur yang hidup dan dijaga oleh masyarakat adat.
Kami berharap ke depan setiap kegiatan kenegaraan yang diselenggarakan di daerah, terutama di wilayah yang memiliki sejarah dan peradaban adat yang kuat, dilaksanakan dengan kepekaan budaya, kearifan dan kebijaksanaan lokal, serta adab yang tinggi. Protokol negara hendaknya tidak semata berpijak pada aturan administratif, melainkan juga memberikan ruang kehormatan yang layak bagi tokoh adat sebagai pemilik nilai dan penjaga sejarah daerahnya.
Kepada para pejabat, aparatur pemerintahan, dan penyelenggara negara, kami mengajak untuk lebih banyak mendengar suara kearifan lokal, membangun dialog dengan tokoh adat, serta menempatkan adat istiadat sebagai mitra sejajar, bukan sekadar pelengkap seremoni.
Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran yang berharga sekaligus momentum perbaikan ke depan, agar Yang Mulia Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagai simbol kehormatan adat dan penjaga sejarah peradaban tidak lagi diperlakukan dengan cara yang tidak patut, di mana pun dan dalam kegiatan apa pun. Sebab pada hakikatnya, pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang menjunjung tinggi adab, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang memahami serta memuliakan rakyat dan nilai-nilai luhur yang hidup di dalamnya. (*Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Laskar Adat Kesultanan Kutai Ing Martadipura Kalimantan Timur)