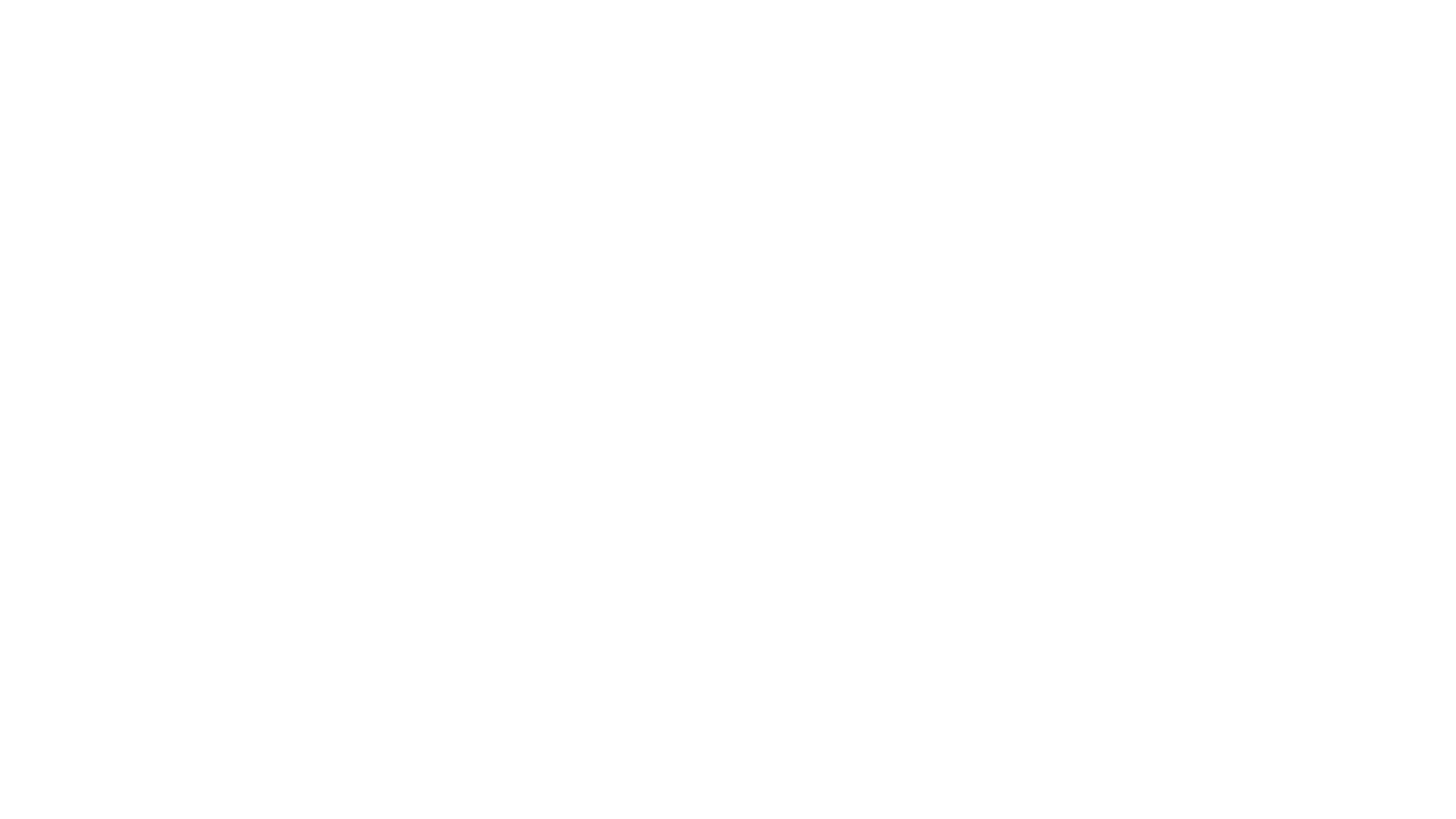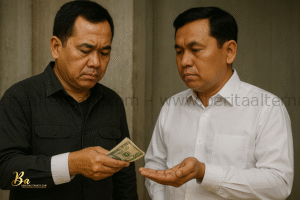Oleh: Rico Fernando Agaki Adadikam*
Ketika mendengar kata “kapal”, banyak orang membayangkan petualangan di laut lepas, transportasi antarpulau, atau deru mesin yang gagah. Tapi ada sisi lain yang jarang sekali disorot yaitu sanitasi kapal serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
Dua hal ini sering dianggap sepele, padahal sangat menentukan keselamatan awak maupun penumpang. Kapal yang terlihat megah sekalipun bisa jadi tempat penyebaran penyakit atau lokasi kerja yang berisiko tinggi bila aspek sanitasi dan K3 diabaikan.
Secara global, sebenarnya aturan tentang kesehatan dan keselamatan di kapal sudah jelas. International Health Regulations (IHR 2005) mewajibkan setiap kapal memiliki Ship Sanitation Certificate, dokumen yang memastikan kapal bebas dari risiko penyakit. Selain itu, Maritime Labour Convention (MLC 2006) juga menekankan pentingnya kondisi kerja, akomodasi, dan layanan medis yang layak bagi awak kapal.
Namun di lapangan, implementasi aturan ini tidak selalu berjalan mulus. Sebuah studi di kapal kontainer Jerman mencatat 33,7% keluhan awak kapal berkaitan dengan penyakit dalam, 19,6% dengan infeksi saluran pernapasan, dan 17,9% akibat kecelakaan kerja (Oldenburg et al., 2023, BMC Public Health). Artinya, meski ada standar internasional, kondisi kerja di laut tetap penuh risiko.
Kita juga pernah mendengar kasus wabah norovirus di kapal pesiar. Virus ini bisa menyebar cepat hanya karena fasilitas sanitasi tidak bersih. Studi menunjukkan, transmisi penyakit di kapal bukan hanya antarmanusia, tetapi juga dari lingkungan kapal itu sendiri—mulai dari toilet hingga ruang makan (Awofeso et al., 2017, International Journal of Environmental Research and Public Health).
Indonesia adalah negara kepulauan yang setiap hari hidup dari transportasi laut. Kapal bukan hanya penghubung antarpulau, tapi juga nadi perekonomian. Sayangnya, kondisi kebersihan kapal (sanitasi) dan keselamatan kerja awaknya masih sering terabaikan.
Di banyak kapal kecil, limbah masih dibuang langsung ke laut, air minum diambil dari tangki tanpa penyaringan, dan fasilitas keselamatan kerja seadanya. Penelitian menunjukkan, kualitas air bersih yang buruk bisa meningkatkan risiko penyakit diare dan infeksi (Rahayu et al., 2022, Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia). Sementara studi global juga menemukan bahwa kecelakaan adalah salah satu penyebab utama awak kapal tidak bisa bekerja di laut (Oldenburg et al., 2023, BMC Public Health).
Masalah ini sering diabaikan karena dianggap beban biaya, sulit diawasi, dan kesadaran awak kapal masih terbatas. Padahal dampaknya nyata: penyakit menular, kecelakaan, turunnya produktivitas, hingga reputasi buruk bagi kapal.
Solusinya sebenarnya sederhana. Pengawasan harus lebih merata, pelatihan awak kapal diperbanyak, fasilitas dasar diperbaiki, dan penelitian lokal terus ditingkatkan. Dengan begitu, kapal tidak hanya jadi alat angkut, tapi juga rumah sementara yang sehat dan aman bagi para awaknya.
Kesimpulannya, sanitasi kapal dan K3 sering kali luput dari perhatian, padahal keduanya sangat menentukan keselamatan awak maupun penumpang. Regulasi internasional seperti International Health Regulations (IHR 2005) dan Maritime Labour Convention (MLC 2006) sudah mengatur hal ini, tetapi praktik di lapangan masih banyak kekurangan. Fakta penelitian membuktikan tingginya angka penyakit dan kecelakaan di kapal, baik di level global (Oldenburg et al., 2023) maupun di Indonesia (Rahayu et al., 2022).
Indonesia yang sangat bergantung pada transportasi laut seharusnya lebih serius memperhatikan aspek ini. Kapal bukan sekadar alat angkut, melainkan juga “rumah sementara” bagi awaknya. Tanpa sanitasi yang layak dan standar K3 yang jelas, kapal bisa menjadi sumber penyakit sekaligus tempat kerja yang berbahaya.
Karena itu, sudah saatnya semua pihak—pemerintah, pemilik kapal, hingga masyarakat—bersama-sama mendorong perbaikan. Mulai dari pengawasan yang lebih merata, penyediaan fasilitas dasar yang memadai, hingga pelatihan rutin bagi awak kapal. Dengan langkah sederhana namun konsisten, kapal dapat menjadi sarana transportasi yang tidak hanya aman, tetapi juga sehat dan manusiawi. (*Mahasiswa Magister Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman)
Referensi
Oldenburg, M., Jensen, H. J., & Wegner, R. (2023). Spectrum of disease and medical consultations on German container ships: a telemedical maritime medicine analysis. BMC Public Health, 23(1).
Awofeso, N., Fennell, M., & Waliuzzaman, Z. (2017). Norovirus outbreaks on cruise ships: a review of epidemiology, clinical features, and prevention. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(9).
Rahayu, S., et al. (2022). Analisis kualitas air bersih pada kapal penumpang di Pelabuhan X. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia (Sinta 2).
WHO. (2005). International Health Regulations (IHR). Geneva: World Health Organization.
International Labour Organization (ILO). (2006). Maritime Labour Convention. Geneva: ILO.