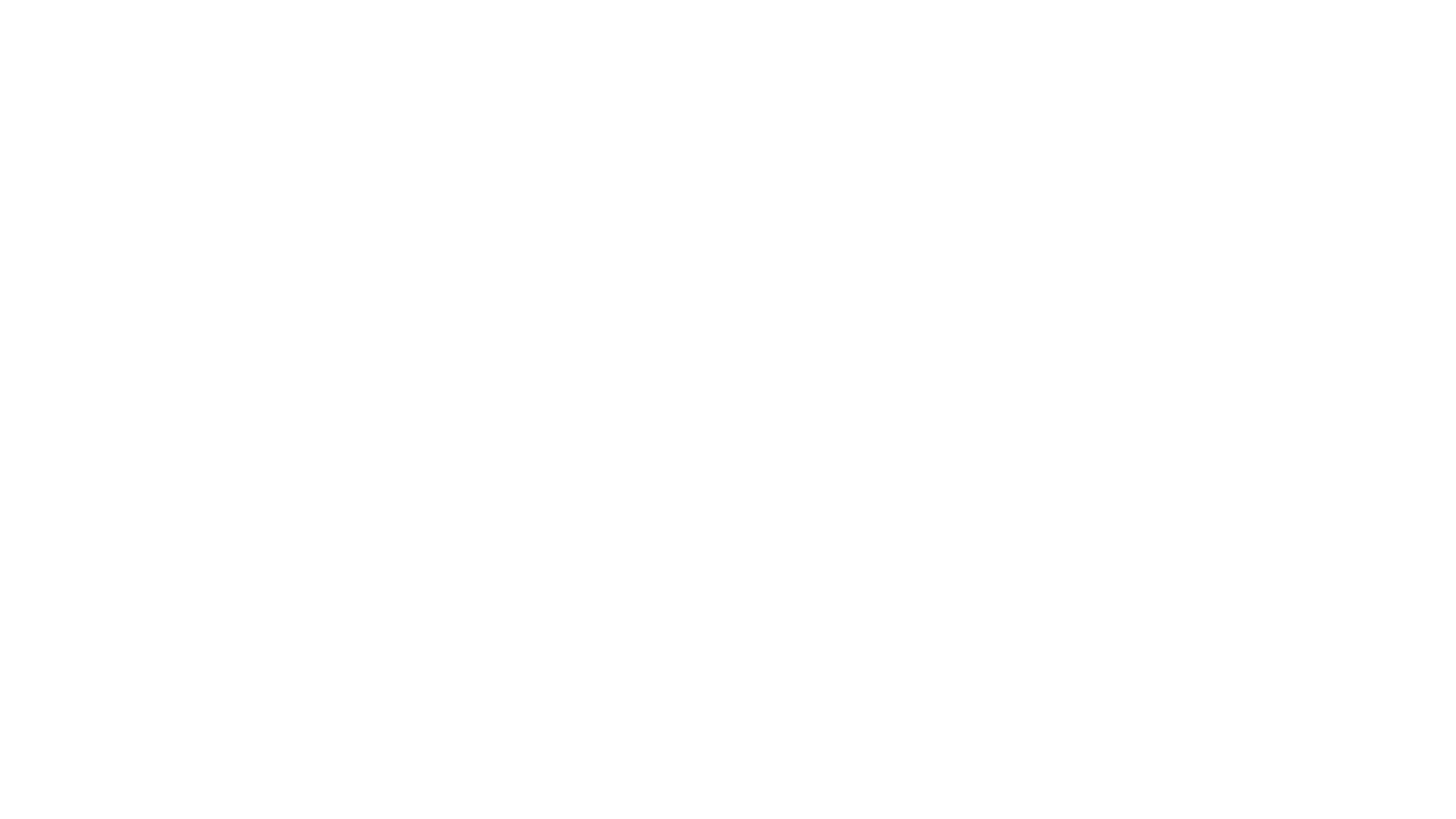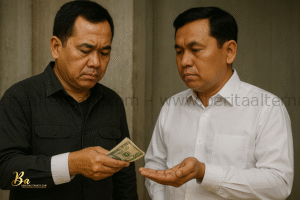Oleh: Boli Matius Tandi Payung*
Di era yang serba cepat ini, digitalisasi bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan yang tidak terelakkan. Hampir semua sektor, mulai dari kesehatan, industri, hingga pendidikan, telah terdampak oleh arus transformasi digital. Salah satu bidang yang mengalami perubahan signifikan adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Digitalisasi menjanjikan efisiensi, akurasi, dan pengawasan yang lebih ketat, namun di sisi lain, ia juga membawa tantangan baru yang perlu diantisipasi.
Bayangkan sebuah pabrik yang dulu bergantung pada pengawasan manual. Para supervisor harus berkeliling area produksi untuk memastikan semua prosedur keamanan diikuti dengan benar. Kini, berkat teknologi digital, sensor pintar dapat dipasang di setiap mesin untuk memantau suhu, getaran, bahkan tingkat kebisingan secara real-time. Data ini kemudian terkumpul dalam satu sistem yang dapat diakses dari layar ponsel atau komputer. Jika terjadi anomali, alarm akan berbunyi dan tindakan pencegahan dapat segera diambil. Inilah salah satu bentuk nyata harapan yang dibawa digitalisasi: mencegah kecelakaan kerja sebelum terjadi.
Lebih dari itu, digitalisasi memungkinkan perusahaan mengelola data K3 secara lebih sistematis. Laporan kecelakaan kerja yang sebelumnya menumpuk di berkas fisik kini dapat tersimpan rapi dalam cloud. Analisis data pun menjadi lebih mudah, sehingga perusahaan bisa mengidentifikasi pola dan risiko yang sering muncul. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa cedera tangan paling sering terjadi pada shift malam, perusahaan dapat segera memberikan pelatihan tambahan atau memperkuat pengawasan di jam tersebut. Dengan kata lain, teknologi membantu membuat keputusan berbasis data yang lebih tepat sasaran.
Tidak hanya di tingkat perusahaan, pemerintah pun dapat memanfaatkan digitalisasi untuk memperkuat regulasi. Aplikasi pelaporan daring memungkinkan pekerja melaporkan pelanggaran K3 secara cepat dan anonim. Sistem ini memberi ruang bagi transparansi sekaligus mempercepat penanganan kasus. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi dunia kerja, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam pengawasan ketenagakerjaan.
Namun, seperti dua sisi mata uang, digitalisasi juga memiliki tantangan yang tidak bisa diabaikan. Pertama, kemunculan risiko baru yang justru berkaitan dengan teknologi itu sendiri. Misalnya, pekerja yang harus berinteraksi dengan mesin otomatis atau robot memerlukan keterampilan baru agar tidak terjadi kecelakaan akibat kesalahan teknis. Selain itu, adanya sistem digital yang terhubung dengan internet membawa ancaman keamanan siber. Bayangkan jika data K3 diretas atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab—dampaknya bisa fatal, baik bagi perusahaan maupun pekerja.
Tantangan lainnya adalah kesenjangan digital. Tidak semua perusahaan memiliki sumber daya untuk mengadopsi teknologi terbaru. Perusahaan besar mungkin mampu memasang sensor canggih dan menggunakan perangkat lunak analisis data, tetapi bagi usaha kecil dan menengah, hal ini masih dianggap sebagai beban biaya yang berat. Akibatnya, terjadi ketimpangan dalam penerapan K3 berbasis digital, yang pada akhirnya justru memperlebar jurang keselamatan antara perusahaan yang mampu dan tidak mampu.
Selain faktor teknis dan finansial, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi isu penting. Pekerja dan manajer perlu diberikan pelatihan yang memadai agar mereka bisa memanfaatkan teknologi dengan optimal. Tanpa pemahaman yang benar, digitalisasi bisa menjadi pedang bermata dua. Misalnya, pekerja yang tidak memahami cara kerja mesin otomatis dapat melakukan kesalahan yang mengakibatkan kecelakaan. Di sinilah pentingnya perusahaan untuk tidak hanya fokus pada pembelian alat, tetapi juga investasi pada pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
Tidak kalah penting, aspek kesehatan mental juga perlu diperhatikan. Dalam era digital, banyak perusahaan yang menerapkan sistem pemantauan ketat berbasis teknologi, seperti pelacakan produktivitas dan penggunaan kamera pengawas. Meskipun hal ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi, namun jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menimbulkan stres dan rasa tertekan pada pekerja. Pekerja mungkin merasa selalu diawasi, yang berujung pada penurunan motivasi dan kesehatan mental.
Pada akhirnya, digitalisasi memang membuka jalan menuju masa depan dunia kerja yang lebih aman dan efisien. Namun, transformasi ini tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan: kesiapan teknologi, kapasitas perusahaan, keterampilan tenaga kerja, hingga dampaknya pada kesejahteraan psikologis pekerja.
Harapan kita adalah agar teknologi benar-benar menjadi alat yang mempermudah, bukan memperumit. Pemerintah, perusahaan, dan pekerja perlu berjalan beriringan dalam proses ini. Regulasi harus terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan teknologi, sementara perusahaan dituntut untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerjanya.
Digitalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai lingkungan kerja yang lebih baik. Tantangannya memang besar, tetapi dengan kolaborasi dan perencanaan yang matang, harapan untuk menciptakan dunia kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan bukanlah hal yang mustahil. Di sinilah kita semua ditantang untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pengelola yang bijak dalam memanfaatkan potensi digital demi masa depan yang lebih cerah. (*Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman)