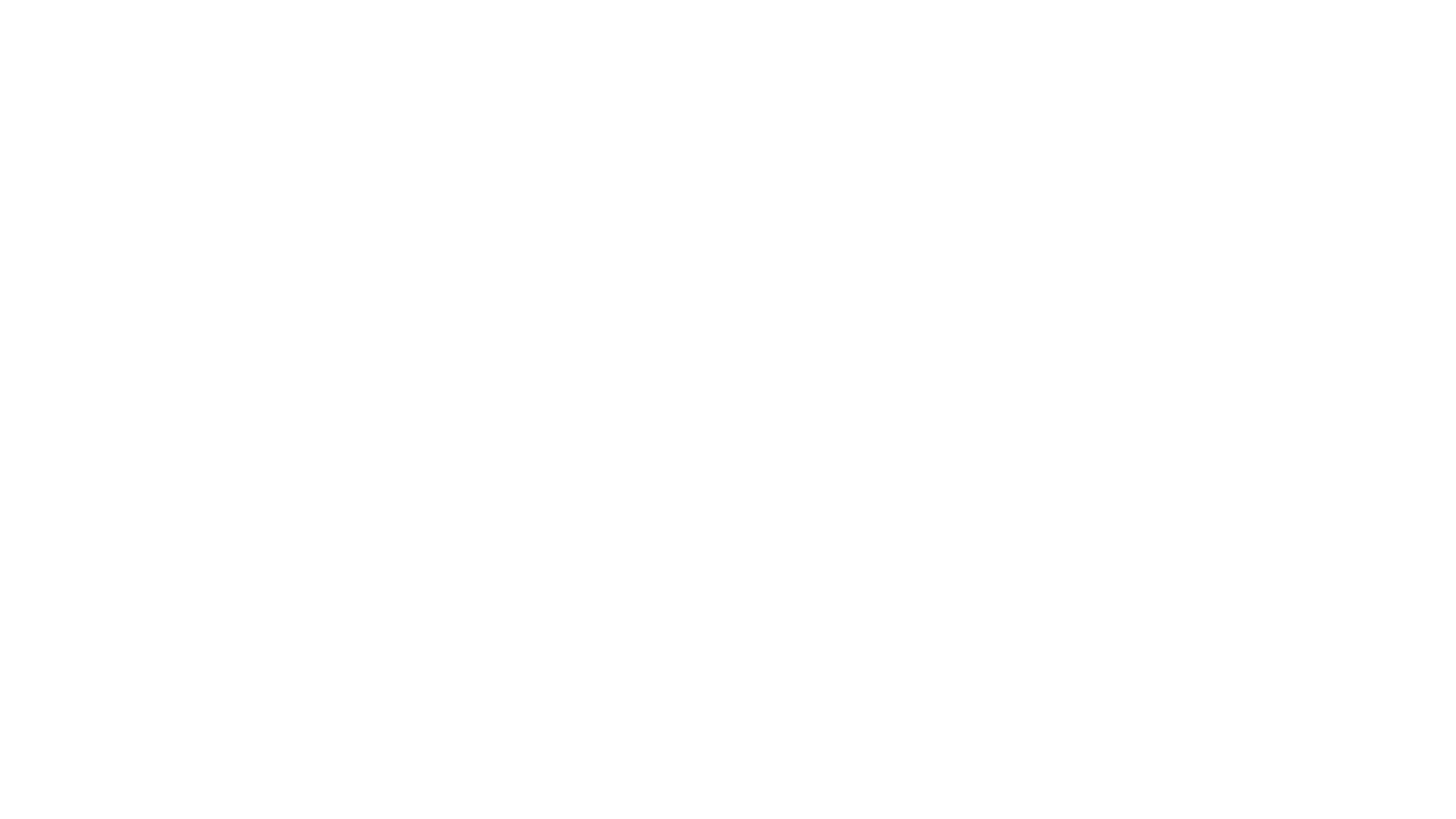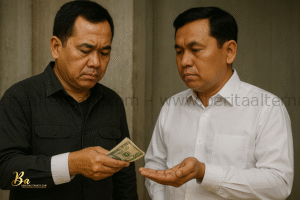Oleh: Muhammad Nur Huda*
Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (MK3) di puskesmas adalah suatu sistem yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi tenaga kesehatan, staf, serta pengunjung puskesmas. Sistem ini melibatkan perencanaan, pembentukan tim K3, pelaksanaan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, serta monitoring dan evaluasi berkala untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Penerapan MK3 di puskesmas sebelum Covid cenderung standar administratif dan teknis “klasik”, sementara setelah Covid, penerapan K3 menjadi jauh lebih dinamis, responsif terhadap risiko infeksi, dan lebih adaptif dengan model K3 berbasis risiko biologis global. Pandemi mempercepat transformasi K3 menjadi prioritas dalam semua lini pelayanan puskesmas, menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja bagian vital dari sistem kesehatan primer di Indonesia.
Berikut ini adalah perubahan sebelum dan sesudah era Covid-19:
Pertama, fokus utama MK3 sebelum Covid-19. Sebelum pandemi, MK3 di puskesmas diarahkan terutama pada aspek pencegahan dan pengendalian risiko cedera, kecelakaan kerja, infeksi nosokomial umum, serta paparan zat kimia dan alat medis. Orientasinya masih sangat administratif dan teknis-konvensional dibanding penekanan pada risiko biologis seperti masa Covid-19.
Kedua, komponen dasar penerapan MK3 meliputi kebijakan dan organisasi, identifikasi dan penilaian risiko, pengendalian dan pencegahan, serta monitoring dan evaluasi.
Ketiga, kegiatan dan indikator kepatuhan, yang meliputi ketersediaan APD di semua area tindakan (sarung tangan, masker, jas lab); kepatuhan cuci tangan pada titik kritis (5 moments of hand hygiene) walau implementasinya cenderung terbatas; penanganan limbah medis: insinerator/transportasi limbah sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup.
Selain itu, pemeriksaan kesehatan rutin petugas: edukasi hepatitis, imunisasi, cek kesehatan berkala, serta simulasi kebakaran, pelatihan pemadaman kebakaran, dan rencana evakuasi sederhana.
Keempat, tantangan penerapan MK3 sebelum Covid-19, antara lain isu utama adalah kepatuhan penggunaan APD masih kurang bila tidak ada supervisi langsung; rendahnya alokasi dana khusus K3, sehingga pasokan APD dan pelatihan berkala terbatas; program K3 sering dianggap sekadar pelengkap/kewajiban administratif, belum dianggap kultur organisasi; pencatatan pelaporan insiden kerja kadang tidak detail dan cenderung underreported, serta perhatian pada infeksi menular udara (airborne) di luar TB masih sangat rendah.
Sementara itu, manajemen K3 setelah era Covid-19 meliputi:
Pertama, transformasi prioritas dan paradigma. Setelah pandemi Covid-19, MK3 di puskesmas mengalami transformasi besar, dari model administratif dan teknis konvensional, menjadi berbasis manajemen risiko biologis dan siaga wabah. Keselamatan petugas kesehatan serta pencegahan penularan penyakit airborne/droplet menjadi fokus utama; protokol K3 diperluas dan diperketat sesuai pedoman nasional dan WHO.
Kedua, komponen kunci penerapan MK3, antara lain: kebijakan dan organisasi: pembentukan tim tanggap K3 pandemi yang bertugas memastikan kepatuhan, penanganan kasus, audit PPI (Pengendalian dan Pencegahan Infeksi), serta pengoordinasian edukasi; sOP K3 diperbarui, penambahan protokol spesifik penanganan infeksi, skrining pasien, triase ruang, perubahan posisi ruangan, pengaturan pasien infeksiud dan non infeksius, surveilans paparan tenaga kesehatan, dan pelaporan harian.
Ketiga, identifikasi dan penilaian risiko, yang meliputi penilaian risiko lebih detail terhadap penularan penyakit berbasis airborne/droplet, rute kontak, serta paparan lingkungan kerja terbuka.jurnal, serta penggunaan matrix risiko, audit kepatuhan APD, dan monitoring insiden infeksi internal.
Keempat, pengendalian dan pencegahan, antara lain penggunaan APD lengkap (masker medis/N95, gown, pelindung wajah, sarung tangan) diterapkan lebih luas: wajib pada seluruh area pelayanan, bukan hanya ruang tindakan, serta penerapan hand hygiene 6 langkah pada semua momen sesuai standar WHO, disediakan cairan antiseptik di setiap ruangan pelayanan dan ruang tunggu pelayanan.
Selain itu, protokol sanitasi dan disinfeksi: ruang, permukaan, peralatan, dan limbah medis didisinfeksi lebih sering (beberapa kali per hari); pengendalian jarak fisik dan modifikasi tata ruang: pembatas ruang tunggu, jalur pasien terpisah, pembatasan pengunjung, serta implementasi telemedicine dan konsultasi daring untuk meminimalkan kontak fisik.
Kelima, monitoring dan evaluasi ketat: audit, supervisi, dan pelatihan rutin SOP K3 pandemi, melibatkan resertifikasi, simulasi kasus, serta penguatan tenaga medis; sistem pelaporan digital: pelaporan paparan, kasus Covid, insiden kerja, serta pelacakan tracing dalam aplikasi online/website puskesmas, serta kesiapan dan pelatihan evakuasi, isolasi tenaga medis, dan prosedur penutupan sementara layanan jika terjadi paparan internal.
Keenam, dukungan psikososial, rekrutmen, dan komunikasi, yang meliputi penanganan stres kerja, burnout, dan perlindungan kesehatan mental petugas menjadi pilar utama, disediakan sesi konseling, dan waktu istirahat, serta komunikasi publik diperkuat: edukasi masif ke masyarakat terkait protokol kesehatan, skenario kerja sama lintas sektor (kelurahan, kecamatan, babinsa dan polisi, dan tokoh masyarakat).
Setelah era Covid-19, indikator kepatuhan MK3 di puskesmas bertransformasi yaitu lebih menekankan pada perlindungan menyeluruh terhadap infeksi droplet/airborne, prosedur pengendalian risiko biologis terintegrasi, dan monitoring kepatuhan sangat ketat serta terdokumentasi secara sistematis.
Perubahan ini menunjukkan MK3 tidak lagi sebagai formalitas, melainkan fondasi utama proteksi dan pelayanan di fasilitas kesehatan primer setelah mengalami krisis pandemi.
Hambatan dan tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah kurang pahamnya sebagian petugas terhadap penularan Covid-19 dan prosedur baru K3. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan forum diskusi dan evaluasi lintas bidang secara rutin, serta pelaksanaan pelatihan mengenai MK3 kepada petugas medis dan pemegang program, dan sosialisasi secara menyeluruh kepada pegawai puskesams secara rutin. (*Mahasiswa Magister Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman)